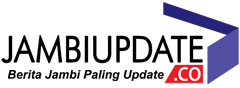Oleh : Noviardi Ferzi
Mirip di Film Action, seorang Presiden negara berdaulat penuh ditangkap di negaranya sendiri. Sulit untuk percaya, tapi itu sudah terjadi Nicolas Maduro ditangkap dalama serangan penuh Amerika di Caracas Ibukota Venezuela, Sabtu dini hari, 3 Januari 2026 kemarin. Presiden Maduro sendiri ditangkap bersama sang istri oleh pasukan Delta Force Pasukan Khusus Angkatan Darat Resmi, tidak pakai proxy atau tangan orang lain.
Tentu saja, sesuai dengan motifnya, eskalasi akan penangkapan Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat yang berujung pada gangguan produksi dan ekspor minyak Venezuela, sementara reaksi dunia yang lain sudah bisa di duga, banyak yang mengecam, banyak juga pura - pura tak tahu, karena ini Amerika Serikat polisi dunia yang bertindak, terlepas salah dan benar, dunia akan lebih mementingkan urusan dalam negerinya pada negara paman Sam tersebut.
BACA JUGA: Kebakaran Hebat di Kasang Pudak, Satu Orang Warga Tewas Terbakar
Lalu, dampaknya secara ekonomi tentu akan jauh melampaui kawasan Amerika Latin, ini yang coba saya kupas dalam tulisan ini. Terlepas dari potensi cadangan migasnya yang berkisar 30 % cadangan dunia, Venezuela memang hanya memproduksi sekitar 800 ribu hingga 1 juta barel minyak per hari, atau kurang lebih satu persen dari total pasokan minyak dunia yang berada di kisaran 100 juta barel per hari.
Namun signifikansi Venezuela tidak terletak pada volumenya semata, melainkan pada struktur pasarnya. Sekitar 65 hingga 75 persen ekspor minyak Venezuela selama beberapa tahun terakhir diserap oleh China, sebagian besar dalam bentuk pembayaran utang energi dan kontrak jangka panjang dengan harga diskon. Artinya, setiap gangguan pasokan Venezuela bukan sekadar mengurangi pasokan global, tetapi langsung memukul strategi ketahanan energi China.
BACA JUGA: Breaking News: DPP Golkar Terbitkan SK Pengurus DPD Golkar Jambi, Cek Endra Resmi Ketua
Bagi China, minyak Venezuela berfungsi sebagai pasokan non-Timur Tengah yang relatif murah dan terikat secara finansial. Jika pasokan ini terganggu, China sebagai importir minyak terbesar dunia—dengan impor harian di atas 11 juta barel—akan dipaksa mencari substitusi dalam waktu cepat. Masuknya China ke pasar spot untuk menutup kekurangan bahkan setengah hingga satu juta barel per hari sudah cukup untuk mengerek harga minyak global.
Pengalaman historis menunjukkan bahwa gangguan pasokan di kisaran 1 persen saja dapat mendorong harga Brent naik 5 hingga 10 dolar AS per barel, terutama dalam kondisi pasar yang sudah ketat akibat konflik Rusia–Ukraina dan ketidakpastian Timur Tengah.
Kenaikan harga minyak global inilah yang menjadi saluran transmisi utama ke Indonesia. Konsumsi BBM nasional berada di kisaran 1,5 juta barel per hari, sementara produksi minyak domestik hanya sekitar 600 ribu barel per hari. Artinya, Indonesia masih mengimpor sekitar 900 ribu barel minyak dan produk turunannya setiap hari.
BACA JUGA: Anggaran Menyusut, Dana Desa Kerinci 2026 Hanya Sekitar Rp300 Juta per Desa
Dengan struktur seperti ini, setiap kenaikan harga minyak sebesar 10 dolar AS per barel berpotensi menambah beban impor energi Indonesia lebih dari 3 miliar dolar AS per tahun. Angka ini langsung berdampak pada APBN karena sebagian besar BBM dan LPG masih disubsidi atau dikompensasi negara.
Dalam APBN, sensitivitas fiskal terhadap harga minyak sangat tinggi. Kenaikan ICP beberapa dolar saja dapat mendorong tambahan belanja subsidi dan kompensasi energi hingga puluhan triliun rupiah per tahun. Jika harga minyak terdorong naik akibat gangguan Venezuela dan lonjakan permintaan China, maka ruang fiskal pemerintah akan semakin sempit. Pilihannya menjadi klasik tetapi berat: menambah subsidi dengan risiko defisit melebar, atau menaikkan harga energi domestik dengan konsekuensi inflasi dan tekanan sosial.
Tekanan fiskal ini beriringan dengan tekanan eksternal. Nilai impor migas yang meningkat akan memperlebar defisit transaksi berjalan dan meningkatkan kebutuhan devisa. Dalam kondisi global yang tidak ramah, situasi ini berpotensi menekan nilai tukar rupiah. Pelemahan rupiah kemudian memperparah imported inflation, karena energi adalah input utama hampir seluruh sektor ekonomi.
Biaya logistik naik, biaya produksi industri meningkat, dan harga pangan terdorong ke atas. Dalam konteks ini, Bank Indonesia cenderung harus mempertahankan kebijakan moneter ketat untuk menjaga stabilitas nilai tukar, yang berarti biaya kredit tetap tinggi dan laju pertumbuhan ekonomi domestik berisiko tertahan.
BACA JUGA: Resmi Jabat Kapolres Kerinci, Ini Profil dan Rekam Jejak AKBP Ramadhanil
Dampak lanjutan yang sering luput diperhitungkan adalah jalur China. Jika China kehilangan pasokan minyak murah dari Venezuela dan harus membeli dengan harga lebih mahal di pasar global, maka biaya energi industrinya akan naik. Perlambatan ekonomi China menjadi risiko nyata. Padahal, lebih dari 20 persen ekspor Indonesia bergantung pada pasar China, terutama untuk komoditas strategis seperti batu bara, nikel, CPO, dan produk mineral lainnya. Jika pertumbuhan China melambat satu persen saja, dampaknya terhadap volume dan harga komoditas Indonesia bisa signifikan, menekan penerimaan devisa dan pendapatan negara.
Dalam satu waktu yang sama, Indonesia berpotensi menghadapi dua tekanan sekaligus, dari sisi pengeluaran melalui lonjakan biaya impor energi dan subsidi, serta dari sisi pendapatan melalui pelemahan ekspor akibat perlambatan China. Inilah yang menjadikan krisis Venezuela—meski secara geografis jauh—sebagai risiko ekonomi yang nyata bagi Indonesia. Minyak Venezuela memang mengalir ke China, tetapi efek akhirnya dapat terasa di neraca perdagangan Indonesia, stabilitas APBN, hingga daya beli masyarakat.
Pada titik ini, isu Venezuela tidak lagi relevan dibaca sebagai konflik ideologis atau politik kawasan. Ia adalah cermin dari rapuhnya ketahanan energi dan tingginya keterkaitan ekonomi global. Setiap gangguan pasokan minyak strategis, sekecil apa pun secara persentase, dapat menciptakan efek berantai yang mahal bagi negara importir seperti Indonesia. Dalam ekonomi global yang saling terhubung, satu juta barel yang hilang di Karibia bisa berubah menjadi tekanan fiskal dan inflasi di Indonesia, dan itu tidak lama, akan segera terjadi.(*)