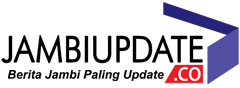Oleh : Dr. Noviardi Ferzi
Predikat sebagai provinsi paling bahagia di Sumatera diangkat lagi ke permukaan. Padahal, data yang digunakan bukanlah data baru, melainkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021. Kala itu, Jambi mencatat skor Indeks Kebahagiaan sebesar 75,17 poin, menduduki peringkat empat nasional.
Padahal, momentum itu tidak lepas dari situasi sosial politik saat itu: masyarakat baru saja keluar dari tekanan pandemi Covid-19, dan harapan akan pemimpin baru hasil Pilkada 2020 masih segar. Namun, pertanyaan sederhana harus diajukan: apakah masyarakat Jambi benar-benar bahagia hari ini, ataukah kita sedang terpukau pada angka yang meninabobokkan? Di saat hari ini mayoritas masyarakat mengerutu karena tak puas akan kinerja Gubernur.
Indeks Kebahagiaan Indonesia yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sejak 2017 dibangun dari tiga dimensi utama, yakni Kepuasan Hidup (Life Satisfaction), Perasaan atau Afektif (Affect), dan Makna Hidup atau Eudaimonia (Meaning of Life). Seluruh indikator ini diukur berdasarkan persepsi subjektif responden. Sebelumnya, pada tahun 2014, BPS hanya menggunakan satu dimensi yaitu kepuasan hidup, kemudian diperluas menjadi tiga dimensi untuk periode 2017–2021 (BPS, 2017; KSAP, 2024).
Dimensi kepuasan hidup mengukur penilaian individu terhadap kondisi kehidupannya secara keseluruhan. Dimensi afektif mengukur perasaan yang dialami sehari-hari, baik positif maupun negatif. Sedangkan dimensi eudaimonia menilai makna hidup, tujuan, serta kendali individu terhadap dirinya. BPS menegaskan bahwa dimensi perasaan dan makna hidup sepenuhnya diperoleh dari ukuran subjektif, sehingga kebahagiaan merupakan “ukuran subjektif terhadap kondisi objektif kehidupan manusia” (BPS Provinsi Riau, 2021). Artinya, penilaian kebahagiaan masyarakat lebih banyak ditentukan oleh faktor persepsi, bukan indikator objektif kesejahteraan.
Di sinilah problem metodologis muncul. Persepsi tidak selalu mencerminkan realitas. Masyarakat yang terbiasa hidup dalam keterbatasan bisa saja merasa puas bukan karena kehidupannya membaik, melainkan karena sudah beradaptasi dengan kondisi sulit dan menganggapnya normal. Dengan kata lain, Indeks Kebahagiaan BPS lebih merefleksikan bagaimana masyarakat menilai dirinya sendiri, bukan kondisi riil sosial-ekonomi yang mereka alami.
BACA JUGA: Arnold Yoseph Pardede, Calon Advokat Muda Berprestasi Dari Jambi Siap Mengabdi Untuk Keadilan
Dalam psikologi sosial, fenomena ini disebut adaptation-level theory—manusia menyesuaikan harapan dengan kondisi yang ada. Maka, ketika warga ditanya soal kebahagiaan, jawaban yang muncul sering kali bukan cermin kesejahteraan nyata, melainkan hasil kompromi batin dengan keadaan.
Ketika kita membuka data yang lebih keras dan faktual, gambaran Jambi justru paradoks. Kemiskinan masih menjadi persoalan kronis. BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jambi Februari 2025 berada di angka 4,48 persen. Penelitian Mawaddah et al. (2023) dan Sari et al. (2024) menunjukkan bahwa pengangguran terbuka berkontribusi signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jambi.
Masalah tidak berhenti di situ. Ketimpangan sosial, konflik agraria, penambangan emas ilegal, hingga kerusakan lingkungan menjadi luka yang kerap luput dari sorotan angka indeks. Semua ini memengaruhi kualitas hidup masyarakat secara langsung, namun tidak tercermin dalam survei persepsi kebahagiaan.
BACA JUGA: Dampak Efesiensi Anggaran, Pemkab Tebo Bakal Rampingkan OPD
Sebagai contoh, penelitian Taufiq et al. (2023) mengungkap bahwa banyak pekerja di Jambi masih berstatus rentan miskin karena rendahnya kualitas pekerjaan. Maka, meskipun ada yang mengaku “puas” dengan hidupnya, kondisi struktural tetap menunjukkan kerentanan sosial yang nyata.
Klaim Jambi sebagai provinsi paling bahagia menjadi janggal ketika dipisahkan dari konteks sosial-ekonomi. Angka indeks memang penting, tetapi tidak boleh berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama indikator lain: kemiskinan, pengangguran, layanan publik, dan kualitas pendidikan.
Tanpa keterhubungan itu, kebahagiaan hanya akan menjadi jargon statistik. Bahagia yang dimaksud bukanlah kebahagiaan substantif, melainkan kebahagiaan semu yang tercatat dalam survei. Bahagia di atas kertas, tapi rapuh di lapangan.